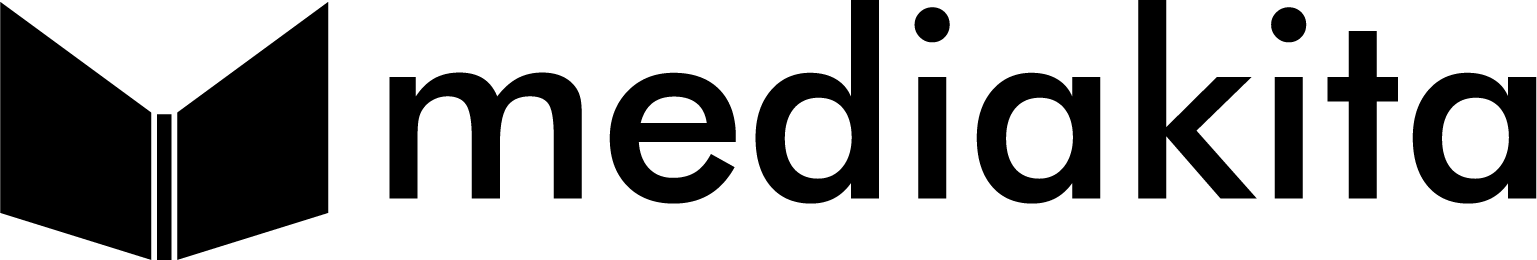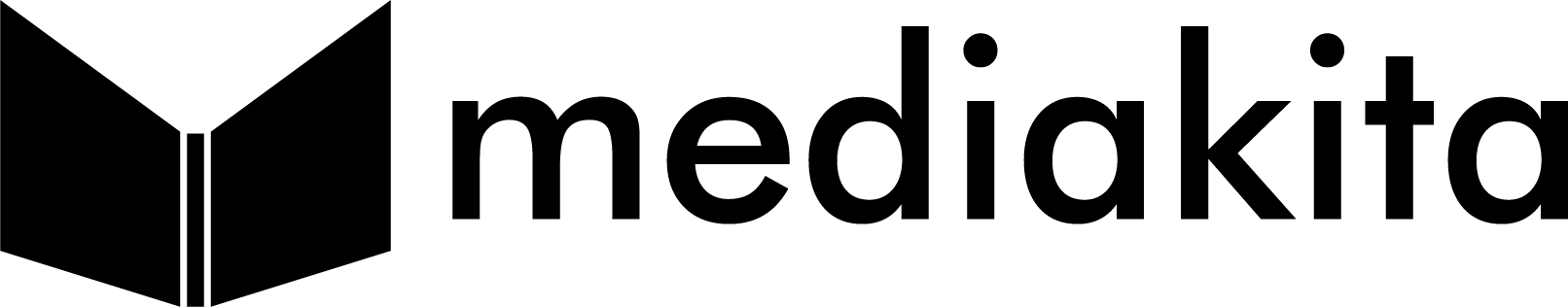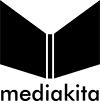Keindahan Simfoni Yang Menyayat Bulan
 Kurnia Effendi pada Koran Tempo, Minggu, 23 April 2006, menuliskan, "Sebagai novel pertama, setelah pada 2005 naskah dramanya sempat menjadi nomine kompetisi Perempuan Penulis Drama yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, Simfoni Bulan cukup menjanjikan sebagai awal karier Feby dalam khazanah sastra."
Kurnia Effendi pada Koran Tempo, Minggu, 23 April 2006, menuliskan, "Sebagai novel pertama, setelah pada 2005 naskah dramanya sempat menjadi nomine kompetisi Perempuan Penulis Drama yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, Simfoni Bulan cukup menjanjikan sebagai awal karier Feby dalam khazanah sastra."
 Siapa yang berani mengatakan menjadi pelacur itu mudah? Kemarilah. Aku ingin meludahinya. Sekarang. Saat ini juga.
Siapa yang berani mengatakan menjadi pelacur itu mudah? Kemarilah. Aku ingin meludahinya. Sekarang. Saat ini juga.
(Feby Indirani, Simfoni Bulan)
KEKERASKEPALAAN Feby Indirani untuk menangkis pendapat ibunya, bahwa ia dianggap tak cocok menulis fiksi, justru melahirkan sebuah karya yang elok: novel Simfoni Bulan. Sebagai novel pertama, setelah pada 2005 naskah dramanya sempat menjadi nomine kompetisi Perempuan Penulis Drama yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, Simfoni Bulan cukup menjanjikan sebagai awal karier Feby dalam khazanah sastra.
Berkisah tentang seorang mantan wartawan yang ingin menulis novel dengan cara mengalami secara langsung, Bulan Rahmatulayla bertekad menjadi pelacur. Dengan mengalami atau terlibat dalam kehidupan nyata yang hendak ditulisnya, Bulan berharap novelnya tidak hadir sebagai omong kosong belaka. Keyakinan itu muncul atas pengaruh Visya Yudhistira, novelis muda yang dikaguminya karena selalu menuliskan pengalamannya. Rasa sakit yang dimaksud dalam setiap novel Visya adalah luka yang secara fisik ataupun psikis telah dialami oleh pengarangnya. Visya selalu memandang sinis pada kehidupan, sementara dia sendiri menjalani hidup secara unik.
Berhasilkah Bulan dengan obsesinya itu? Agaknya ada serangkaian kegagalan yang sejak awal telah membayangi hidup Bulan. Boleh jadi dia lahir dari keluarga yang berantakan. Berbekal hubungan buruk dengan ibunya, ia membenci kata "pulang". Ketika bekerja pada sebuah tabloid berita dan dipercaya menjadi asisten pemegang rubrik, ia dianggap tidak mampu menulis.
Sifat keras kepala sang pengarang agaknya menurun kepada tokoh novelnya, yang ditandai dengan pengambilan keputusan untuk keluar dari pekerjaannya hanya lantaran perbedaan pendapat dengan atasannya. Pengalamannya meliput daerah prostitusi di Kramat Tunggak membuatnya ingin mengangkat tokoh pelacur turun-temurun dalam sebuah novel. Namun, itu ternyata tak semudah yang diharapkan karena selama ini dia biasa menulis berdasarkan fakta dan data. Bekal imajinasinya tak sanggup menjangkau atmosfer yang hendak dituangkan.
Menjadi pelacur adalah keputusan besar berikutnya, yang sempat mengagetkan Steve, sahabatnya yang kemudian menjadi manajernya. Ternyata menjalani kehidupan pelacur secara profesional tak hanya sulit saat awalnya, bahkan beberapa pengalaman menerima tamu berikutnya menunjukkan betapa tak berharganya seorang pelacur di mata laki-laki. Ia harus mengorbankan harga diri sekaligus menyaksikan berlangsungnya kemunafikan kaum lelaki yang kadang-kadang menjadi idola di tengah masyarakat.
Proses "kelahiran" kembali seorang Bulan, sebagai spirit reinkarnasi, memang hendak diawali dengan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai titik balik. Tapi masa lalunya yang kelam tak benar-benar lenyap terkubur. Ada jejak tersisa sebagai bagian dari eksistensi yang pernah diperjuangkan dengan mempertaruhkan harga diri. Ini justru tercium kembali aromanya melalui peristiwa book-signing yang tak termaafkan baginya. Selanjutnya, kita sebagai pembacalah yang bertugas membayangkan akhir cerita.
Banyak hal menarik dari novel Simfoni Bulan. Pertama, Feby tidak bercerita secara linier. Ia meletakkan beberapa kilas balik yang berfungsi saling menjelaskan. Kedua, ia tidak menciptakan tokoh hitam dan putih, melainkan abu-abu. Manusiawi dan realistis: bahkan tokoh Bulan yang selayaknya kita bela karena serangkaian beban penderitaannya itu pun bukan orang suci di mata Tuhan. Ketiga, sebagaimana definisi sebuah novel (seraya mengingat kembali pelajaran sastra di bangku sekolah menengah), tokohnya mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Syarat ini juga dipenuhi oleh sang pengarang. Keempat, banyak kejutan yang tak terasa sengaja diletakkan, tapi menunjukkan bahwa setiap kejadian di belakang memiliki musabab.
Seperti umumnya novel yang ditulis oleh jurnalis atau seseorang yang bergelut dalam dunia riset untuk media massa, cerita terasa cerdas dan memiliki logika fiksi yang baik. Karakter tokoh cukup kuat, terutama tecermin pada sikap Bulan terhadap ibunya meski telah dibayar dengan rasa kehilangan. Artinya, ada kemungkinan melodramatis yang justru tidak dipilih oleh Feby, yang sekaligus telah menyelamatkan novel ini dari sikap ambigu.
Ketidaksepakatan saya mungkin terdapat pada pertanyaan Bulan di awal profesinya sebagai pelacur: "Kalau aku dipromosikan sebagai pelacur yang mantan wartawan, akan menambah nilai jualku nggak?" Jawaban Steve boleh jadi benar, tapi secara umum wartawan–meskipun mantan–tidak sekadar "ditakuti" karena lebih pintar ngomong: jauh lebih mencemaskan apabila perilaku pemakai jasa seks kelas tinggi, yang acap menjadi figur publik, akan bocor ke tengah masyarakat. Hal yang lain adalah "sebuah kebetulan" yang nyaris mengganggu, saat Visya menyelamatkan Bulan di sebuah rumah sakit. Boleh jadi benar, "rumah" kedua bagi Visya yang kerap melukai diri sendiri adalah rumah sakit, tapi terlalu banyak rumah sakit di Jakarta untuk sebuah keberuntungan. Sementara itu, di halaman 72 Feby seperti membuat laporan dengan memindahkan data observasi yang diperoleh dari hasil statistik.
Meskipun novel karya Feby Indirani ini hampir merupakan kisah yang mencurahkan nasib sedih berturut-turut kepada tokoh utamanya, sang pengarang tidak memberi judul Elegi Bulan, tapi Simfoni Bulan. Bagi tokoh yang selalu gagal (Aku mungkin cuma orang gagal. Wartawan gagal. Pengarang gagal. Pun sekarang jadi pelacur gagal), metafor "simfoni" terasa lebih mencerminkan keindahan dan mengandung optimisme ketimbang "elegi". Hidup yang dramatik dengan melewati segala kepedihan itu terdengar serupa lagu merdu, sebagai pemberian Tuhan, meskipun merajang perih. Sesuai dengan namanya tentu, Bulan Rahmatulayla, bulan sebagai anugerah malam, keindahan di tengah kelam?
Tulisan ini dimuat di Koran Tempo, Minggu, 23 April 2006
* KURNIA EFFENDI, PENULIS, PENCINTA SASTRA, TINGGAL DI JAKARTA