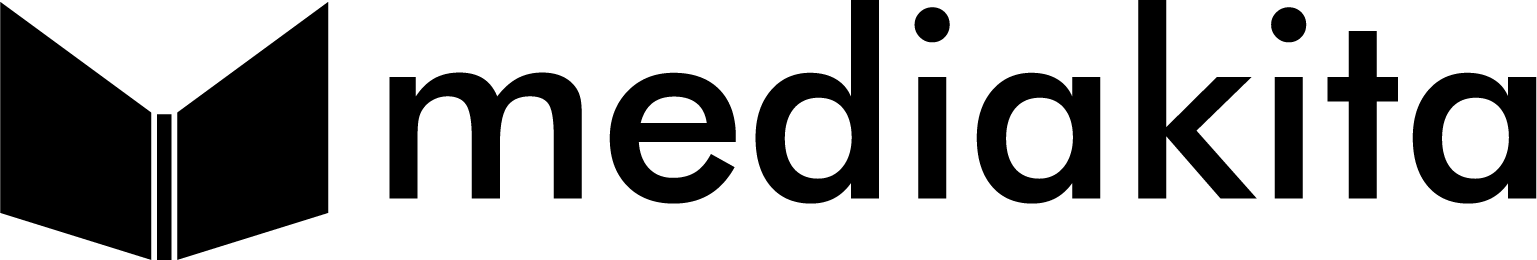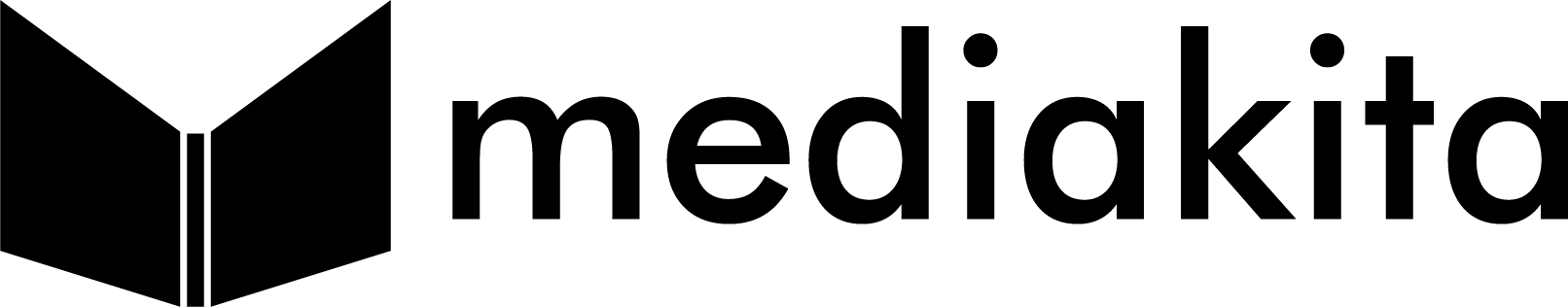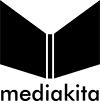Mengalami Pelacuran dalam Simfoni Bulan

 Sama-sama berhenti jadi wartawan untuk menulis buku. Itulah kesamaan antara Bulan Rahmatulayla, tokoh utama dalam novel Simfoni Bulan, dan Feby Indirani, penulisnya. Bulan terjun langsung menjadi pelacur untuk mengenali dunia yang hendak dinovelkannya. Feby? Novel Simfoni Bulan memang saya awali dengan kata mengalami, kata Feby. Ikuti wawancara dengan Feby tentang proses kreatif novelnya.
Sama-sama berhenti jadi wartawan untuk menulis buku. Itulah kesamaan antara Bulan Rahmatulayla, tokoh utama dalam novel Simfoni Bulan, dan Feby Indirani, penulisnya. Bulan terjun langsung menjadi pelacur untuk mengenali dunia yang hendak dinovelkannya. Feby? Novel Simfoni Bulan memang saya awali dengan kata mengalami, kata Feby. Ikuti wawancara dengan Feby tentang proses kreatif novelnya.
Wawancara dengan Feby Indirani, penulis novel Simfoni Bulan
 Setelah lima tahun bekerja sebagai wartawan, Bulan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan berniat menyelesaikan penulisan novelnya tentang perempuan pelacur. Ia memang dekat dengan beberapa pelacur di Kramat Tunggak semasa menjadi wartawan dan bahkan mengasuh anak semata wayang dari seorang pelacur yang mati terbunuh. Namun empati saja ternyata tidak memadai sebagai bekal untuk menulis novel. Terhantui oleh kata-kata Visya, penulis yang dikaguminya, mengenai mengalami karakter yang akan ditulis, Bulan akhirnya memutuskan untuk melakukan observasi-partisipatoris: melakoni profesi pelacur. Dengan bantuan Steve, sahabatnya, ia akhirnya terjun sebagai pelacur kelas atas, bukan pelacur kelas Kramat Tunggak yang menjadi inspirasi awalnya menulis novel. Pada saat itulah ia terbanting-banting oleh ganasnya persaingan, frustrasi karena tidak mumpuni sebagai pelacur dan tidak cakap sebagai penulis. Di luar itu, pembunuhan pelacur sahabatnya tetap membayang-bayangi perjalanannya hidupnya.
Setelah lima tahun bekerja sebagai wartawan, Bulan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan berniat menyelesaikan penulisan novelnya tentang perempuan pelacur. Ia memang dekat dengan beberapa pelacur di Kramat Tunggak semasa menjadi wartawan dan bahkan mengasuh anak semata wayang dari seorang pelacur yang mati terbunuh. Namun empati saja ternyata tidak memadai sebagai bekal untuk menulis novel. Terhantui oleh kata-kata Visya, penulis yang dikaguminya, mengenai mengalami karakter yang akan ditulis, Bulan akhirnya memutuskan untuk melakukan observasi-partisipatoris: melakoni profesi pelacur. Dengan bantuan Steve, sahabatnya, ia akhirnya terjun sebagai pelacur kelas atas, bukan pelacur kelas Kramat Tunggak yang menjadi inspirasi awalnya menulis novel. Pada saat itulah ia terbanting-banting oleh ganasnya persaingan, frustrasi karena tidak mumpuni sebagai pelacur dan tidak cakap sebagai penulis. Di luar itu, pembunuhan pelacur sahabatnya tetap membayang-bayangi perjalanannya hidupnya.
 Selesai membaca Simfoni Bulan, otak saya tergoda untuk membandingkan Feby Indirani, sang penulis, dengan Bulan Rahmatulayla, karakter utama dalam novel tersebut, seorang feminis yang berbadan mungil, berbicara tegas, dan jarang tersenyum. Saya jadi penasaran, ingin bertemu dengan Feby dan membuktikan apakah bayangan saya memang benar. Apalagi, gadis kelahiran Jakarta, 15 Februari 1979, itu baru saja memutuskan pensiun sementara jadi wartawan dan bekerja sebagai periset di Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT) karena merasa tidak memiliki waktu untuk membaca dan menulis bagi dirinya sendiri. Sore itu, Selasa 20 Februari 2006, seorang wanita mungil dengan suara manja datang menepati janji wawancara kami.
Selesai membaca Simfoni Bulan, otak saya tergoda untuk membandingkan Feby Indirani, sang penulis, dengan Bulan Rahmatulayla, karakter utama dalam novel tersebut, seorang feminis yang berbadan mungil, berbicara tegas, dan jarang tersenyum. Saya jadi penasaran, ingin bertemu dengan Feby dan membuktikan apakah bayangan saya memang benar. Apalagi, gadis kelahiran Jakarta, 15 Februari 1979, itu baru saja memutuskan pensiun sementara jadi wartawan dan bekerja sebagai periset di Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT) karena merasa tidak memiliki waktu untuk membaca dan menulis bagi dirinya sendiri. Sore itu, Selasa 20 Februari 2006, seorang wanita mungil dengan suara manja datang menepati janji wawancara kami.
Bulan berhenti jadi wartawan untuk melakukan observasi-partisipatoris; Feby juga berhenti jadi wartawan, untuk
?
(Feby tersenyum) Menyelesaikan novel gua.
Apa, seperti Bulan, kamu juga melakukan observasi-partisipatoris untuk menyelesaikan novel ini?
(Feby menjawab dengan diam.)
Apa yang menjadi dorongan utama menulis novel ini?
Gua suka sebel dengar orang menyampaikan simpati dengan bilang, Gue ikut merasakan kesedihan lu. Really? Menurut gua, mana kita tahu perasaan orang lain kalau kita tidak pernah mengalami sendiri? Selain itu, ada juga kalimat: Pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi kita tidak perlu mengalami sendiri, cukup dari pengalaman orang lain. Apa lagi cara belajar yang paling baik, selain mengalaminya sendiri? Sebetulnya pengalaman itu memperkaya. Dan kita akan lebih kaya kalau kita sudah pernah mengalami semuanya itu sendiri.
Jadi, kamu memang memulai novel ini dari kata mengalami?
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang gua mempunyai keprihatinan terhadap Kramat Tunggak.
Waktu saya baca bagian-bagian itu”Kramat Tunggak”saya memang merasakan kalau ini semacam essai pribadi kamu.
Gua memang biasanya menulis essai. Karena cara berpikir dan opini-opini gua yang radikal, biasanya essai gua dimuat di tabloid-tabloid independen. Essai gua sering dimuat di tabloid milik sebuah organisasi feminis.
Soal Kramat Tunggak, gua punya pandangan sendiri. Gua merasakan ada semacam keangkuhan orang beragama. Dengan mengatasnamakan agama, mereka mencoba mensucikan tanah hitam dengan cara yang sangat implisit, dengan meletakkan simbol-simbol agama (di bekas lokalisasi Kramat Tunggak, di bangun sebuah masjid dan Islamic Center) tanpa memikirkan aspek lain di luar moral dan akhlak. Mereka enggak pernah mikirin orang-orang yang bekerja di sana mau dikemanakan. Pelacur-pelacur di sana, tukang rokok, tukang minuman, sampai tukang parkir; Kramat Tunggak bagaimanapun telah menghidupi puluhan ribu orang, puluhan ribu manusia. Kemudian kegiatan perekonomian di sana hilang begitu saja.
Bagaimana pandangan kamu sendiri mengenai pelacurannya?
(Feby seperti enggan menjawab langsung) Ada di novel saya.
Feby mengatakan bahwa ia ingin seperti penulis Italia, Susan Tamaro, yang terkenal di bukunya yang keempat. Atau Seno Gumira, yang buku pertamanya tidak diketahui kebanyakan orang. Ia tidak setuju pada publisitas berlebih terhadap penulis perempuan yang, menurutnya, pada akhirnya justru mematikan kreativitas.
Ngomong-ngomong soal penulis perempuan, dengan terbitnya Simfoni Bulan, berarti ada satu lagi penulis perempuan yang masuk ke dalam industri perbukuan. Bagaimana rasanya memasuki keramaian?
Enggak masalah. Menurut gua keramaian itu bagus. Masak gara-gara semua orang melakukannya, gua jadi enggak mau menerbitkan karya gua sendiri? Kalau minat menulis tumbuh, berarti minat membaca juga sedang tumbuh. Artinya bagus, kan? Abad ke-5, pertamakali orang mencetak buku, sekali cetak 500 eksemplar. Di Indonesia saat ini, beberapa abad kemudian, sekali cetak baru 3.000 eksemplar. Tapi gua melihat beberapa tahun belakangan industri perbukuan kita membaik. Minat menulis tumbuh; semoga juga minat membaca. Sayangnya, dibalik minat itu, masih ada budaya instannya. Semua orang ingin menulis dengan niat jadi selebritis. Ingin menulis novel, ingin difilmkan, ingin dikenal di mana-mana.
Bukankah itu risiko yang harus ditanggung penulis jika bukunya bagus?
Itu gua setuju. Tapi publikasi berlebihan buat penulisnya sendiri enggak baik. Pujian berlebih itu memberatkan, lho. Kita jadi terbebani oleh harapan-harapan orang lain. Selalu punya ketakutan, Buku selanjutnya bagus atau tidak. Lebih bagus dari pada buku sebelumnya atau tidak. Atau malah lebih jelek. Ujung-ujungnya, itu cuma membuat penulis tidak berani berkaya. Kondisi itu juga, dalam beberapa kasus, membuat kreativitas mandek. Tidak berani bereksplorasi. Gua melihat ada beberapa penulis perempuan yang, setelah terkenal, malah memilih status-quo. Karena tulisannya yang seperti itu yang disukai, ya nulisnya jadi gitu-gitu saja.
Jadi, kamu ingin jadi penulis perempuan yang seperti apa?
Penulis perempuan yang setia berkarya, berani bereksplorasi, dan tetap eksis. Buat gua, menerbitkan buku adalah jalan marathon yang harus dilalui step-by-step.
Anak bungsu dari empat bersaudara ini memulai kesukaannya menulis saat diusia 8 tahun ikut-ikutan kakak-kakaknya menulis diary. Dari sana ia jadi senang menulis. Lalu mencoba mengikuti berbagai lomba menulis. Baru di SMU ia menjadi juara kedua untuk perlombaan menulis essai di majalah Gadis. Memenangkan uang sebesar lima ratus ribu dan jalan-jalan ke Toraja membuat Feby menyadari bahwa menulis dapat menghasilkan sesuatu. Karena itu dia memilih kuliah di jurusan jurnalistik, Universitas Padjajaran. Semasa kuliah pun, ia pernah memenangkan lomba menulis essai Toyota Astra. Tahun lalu, ia menjadi salah satu peserta yang mendapatkan beasiswa penulisan dari Agromedia Group di Jakarta School.
Sebagai seorang wartawan, tanpa mengikuti beasiswa penulisan tersebut, bukankah kamu sudah cukup mahir mengolah kata-kata?
Gua orangnya perfeksionis-negatif. Kalau tidak ada paksaan, pasti gua enggak akan bisa bisa menyelesaikan novel ini. Makanya gua ikut pogram ini, supaya ada paksaan dari luar untuk menyelesaikan penulisannya. Pra-gagas-nya udah gua miliki sebelum ikut beasiswa. Di Jakarta School, gua benar-benar belajar membangun cerita, menyusun plot, dan membentuk karakter-karakter. Ternyata enggak semudah yang gua bayangkan. Setidaknya menurut gua, enggak semudah menulis essai, lah. Apalagi ada proses mengkombinasikannya semuanya dengan hasil riset gua.
Seperti apa seorang perfeksionis-negatif menulis?
Setiap kali menulis, edit. Setiap kalimat, edit. Setiap kata, edit. Seperti itu. Oleh pengajar di Jakarta School gua dikasih solusi, Free writing aja dulu, Feb, baru diedit. (Feby tersenyum malu-malu) Tapi, buat gua tetap aja susah ngikutin saran free writing itu.
Kalau caranya seperti itu, susah dong untuk maju ke novel selanjutnya?
Kalau soal ide, saat ini sudah banyak yang gua tabung. Buanyak buanget.
Sudah ada yang mulai kamu kerjakan?
Gua sedang mempersiapkan chicklit.
Kamu nggak takut dibilang ikut-ikutan?
Enggak. Gua enggak begitu kuatir apa yang dipikirkan orang. Gua enggak pengen mengkotak-kotakkan diri. Pada akhirnya orang akan melihat bukan penulisnya, tapi apa yang ingin dia sampaikan. Gua cuma ingin jadi penulis yang punya sesuatu untuk disampaikan ke pembacanya melalui tulisannya.
Feby mengaku, ia memilih menulis karena merasa, sebagai seorang generalis, ia tidak perlu setia pada satu bidang tertentu. Ia ingin mempelajari apa saja untuk memuaskan keingintahuannya dan memperkaya novelnya. Seperti saat ia bilang akan menulis chicklit dengan perspektif ahli serangga, buat Feby berarti ia punya fak baru untuk dipelajari.
Bukankah ada lompatan besar dari novel yang kamu garap serius ke literatur pop?
Soal chicklit itu tidak serius, gua rasa itu soal cara penyampaian saja; gayanya ringan, sederhana, dan lucu. Seperti, In Her Shoes-nya Jennifer Weiner. Dalam novel itu, ada masalah-masalah nyata yang dihadapi dua orang kakak-beradik. Ada konflik-konflik serius dari masing-masing tokohnya. Tidak sekadar konflik cinta melulu. Di buku itu, diceritakan bagaimana sang adik yang menderita dyslexia (gangguan memahami tulisan) mengatasi ketakutannya dengan membaca puisi. Cerita itu sweet sekali, tapi juga lucu. Bagi gua, menyampaikan sebuah gagasan tanpa harus menjadi serius adalah sebuah tantangan.